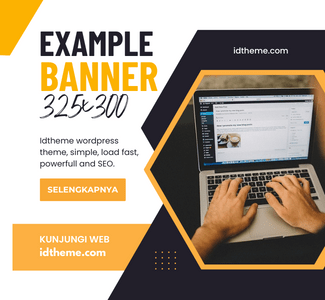Amnesty International Indonesia: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Situasi HAM Mengalami Erosi Terparah
Jakarta, Intelposts.com
Kondisi hak asasi manusia (HAM) setahun pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengalami erosi terparah akibat maraknya kebijakan, tindakan, dan praktik-praktik otoriter, kata Amnesty International Indonesia hari ini.
Erosi hak-hak asasi manusia disebabkan oleh pembuatan kebijakan yang populis dan tidak partisipatif, yang terus menjadi pilihan utama alih-alih dialog dengan warga. Dialog baru menjadi pilihan saat protes meluas, atau saat telah jatuh korban.
Di sektor politik, kebijakan itu ialah remiliterisasi ruang sipil dan pemerintahan, revisi UU TNI, penulisan ulang sejarah, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional, hingga Perkapolri. Di sektor ekonomi, ada resentralisasi, proyek strategis nasional, makan bergizi gratis, pemotongan anggaran daerah (TKD) hingga kenaikan fasilitas anggota parlemen.
“Sejak dilantik 20 Oktober 2024, tidak ada kemajuan berarti untuk hak asasi, baik bebas dari rasa takut maupun dari rasa kekurangan. Sebaliknya, terjadi erosi terparah sepanjang masa reformasi. Kebijakan yang pada masa pemerintahan lalu melanggar hak asasi justru berlanjut. Polanya sama, tanpa partisipasi aktif warga,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
*Erosi hak-hak sipil dan politik*
Setiap manusia, termasuk saat mengekspresikan kritik dan protes, berhak atas perlakuan manusiawi. Tapi setahun terakhir, 5.538 orang jadi korban penggunaan kekuatan eksesif dan kekerasan aparat lainnya saat memprotes pengesahan UU TNI pada Maret 2025, menuntut kesejahteraan buruh pada Mei 2025, dan menolak kenaikan tunjangan DPR RI pada Agustus 2025. Rinciannya, penangkapan (4.453 korban), kekerasan fisik (744 korban), dan penggunaan water canon dan gas air mata (341 korban).
Pasca demo Agustus 2025, saat ini 12 aktivis ditahan sebagai tersangka penghasutan dan dua orang dilaporkan masih hilang. Negara juga tidak serius mengusut jatuhnya 10 korban jiwa saat unjuk rasa Agustus lalu.
“Tim Gabungan Pencari Fakta juga batal dibentuk. Padahal itu amat penting untuk membongkar aktor yang paling bertanggungjawab. Komite Reformasi Polri juga menguap,” kata Usman.
“Bukannya mengevaluasi kebijakan, termasuk memastikan akuntabilitas polisi, Presiden malah memunculkan label negatif “anarkis”, “makar”, “asing”, bahkan “teroris” kepada pengunjuk rasa. Padahal mereka adalah mahasiswa, pelajar sekolah, pegiat literasi, dan warga biasa,” lanjut Usman.
Munculnya Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Polri pada 29 September lalu justru melonggarkan wewenang polisi, terutama penggunaan senjata api.
Sementara itu, kasus kekerasan aparat yang tidak terkait demonstrasi juga marak terjadi. Setidaknya 119 korban kekerasan aparat. Rinciannya, penangkapan (13 orang), kekerasan fisik (93 orang), penyiksaan (27 korban), penembakan (9 orang), pemerasan (5 orang), dan pembunuhan di luar hukum (42 orang). Data ini belum termasuk kasus di Papua yang saat ini sedang diverifikasi.
Di luar penanganan unjuk rasa dan kekerasan aparat, erosi kebebasan sipil lainnya adalah serangan ke pembela HAM berlanjut, yaitu 268 kasus. Dari pelaporan ke polisi (46 korban), penangkapan (17 korban), kriminalisasi (35 korban), percobaan pembunuhan (6 korban), serangan fisik (153 korban), hingga serangan ke tempat kerja pembela HAM (11 lembaga).
Jurnalis dan pegiat adat mengalami serangan terbanyak, masing-masing 112 korban dan 81 korban. Ini termasuk teror bom molotov ke kantor media Jubi di Jayapura, Papua, pada 16 Oktober 2024, yang melibatkan militer tapi justru menguap. Di ranah digital, 14 jurnalis dan lembaga media mengalami serangan. Ini belum termasuk 20 kasus kriminalisasi yang dituduh melanggar UU ITE (26 orang korban).
Represi terus berlanjut di Papua. Ini meliputi kasus penangkapan pada April lalu di Sorong dan pengadilan pasal makar di akhir Agustus, penggunaan gas air mata yang menewaskan warga di kota Manokwari hingga penangkapan lima orang pemrotes investasi dan remiliterisasi di Kota Jayapura, 15 Oktober lalu.
“Apa pun alasannya, manusia berhak atas perlakuan manusiawi. Apalagi jika menyatakan wacana kritis di ruang sipil. Jika ada pembungkam suara-suara kritis oposisi maka yang terbangun adalah atmosfer ketakutan,” kata Usman.
Erosi kebebasan juga diwarnai diskriminasi agama, yaitu 13 kasus. Rinciannya, penyegelan rumah ibadah (7 kasus), intimidasi/pembubaran kegiatan jemaat (5 kasus), dan individu (1 kasus). Ada tiga kasus yang mayoritas korban ialah remaja dan anak; Riau (anak kelas 2 SD dilaporkan meninggal terkait perundungan SARA), Cidahu (retret siswa kristiani dibubarkan paksa) dan Padang (intoleransi pada anak-anak kasus di GKSI). Ironinya, Kementerian HAM saat itu mau ajukan penangguhan penahanan tersangka perusakan kasus Cidahu. Rencana itu batal setelah menuai kritik keras.
Terakhir, erosi hak-hak sipil juga tercermin dari vonis mati yang berlanjut. Meski Presiden telah mengutarakan secara publik ketidaksetujuannya atas hukuman mati, pengadilan negeri di Indonesia masih terus menjatuhkan vonis mati baru pada 56 terdakwa.
Lalu ada Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang masuk dalam prioritas pembahasan DPR RI 2025. Alih-alih menghapus hukuman mati, negara justru sibuk mencari ‘cara alternatif’ untuk hukuman yang jelas kejam.
“Tidak ada bukti bahwa hukuman mati menimbulkan efek jera. Kami sejak lama mendesak Indonesia segera menghapuskan hukuman mati dan menggantinya dengan hukuman yang lebih adil dan manusiawi,” kata Usman Hamid.
*Hak ekonomi, sosial dan budaya semakin tergerus*
Sementara itu erosi hak-hak sosial tercermin dari arah kebijakan yang semakin menjauh dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah, yang jadi program andalan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak, justru memunculkan masalah baru bagi kesehatan siswa dengan maraknya kasus-kasus keracunan massal.
Laporan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 12 Oktober lalu mencatat, sedikitnya 11.566 anak sekolah jadi korban keracunan, diduga pasca menyantap MBG.
Kasus keracunan massal akibat program MBG ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak anak, khususnya atas kesehatan dan perlindungan, sesuai Konvensi Hak Anak dan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1).
Kegagalan negara ini terlihat dari sistem pengawasan yang lemah, pengabaian standar keamanan pangan, serta penanganan program yang sentralistik dan militeristik, yang menyebabkan kerugian bagi anak-anak penerima manfaat.
Lalu pernyataan Prabowo yang menilai statistik keracunan MBG hanya 0,0007 persen dan program MBG 99,99 persen sukses patut dikritik. Pendekatan itu mengabaikan hak dasar setiap anak atas kesehatan dan keselamatan tanpa diskriminasi.
“Satu anak yang menderita pun tidak boleh diabaikan atas nama keberhasilan mayoritas. Pemerintah harus segera meninjau ulang program MBG tersebut untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi,” kata Usman Hamid.
Kedua, proyek-proyek strategis nasional dan industri ekstraktif terus mengorbankan hak masyarakat adat dan lingkungan.
Sejumlah kasus, seperti proyek lumbung pangan nasional di Merauke, Papua, tambang nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara, proyek geotermal di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur serta tambang batu bara di berbagai wilayah sering kali menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Masyarakat adat, jurnalis hingga aktivis bersuara kritis atas proyek-proyek itu mengalami represi dan kriminalisasi.
“Fakta-fakta di atas menunjukkan satu tahun pemerintahan Prabowo memperlihatkan wajah pembangunan yang elitis, eksploitatif, dan jauh dari prinsip keadilan sosial,” kata Usman Hamid.
“Besarnya ketimpangan ekonomi masyarakat menunjukkan kenyataan bahwa pemerintah gagal mewujudkan keadilan sosial. Ketimpangan itu pula yang selama ini terus disuarakan masyarakat lewat aksi-aksi protes, namun negara sering menanggapinya secara represif” kata Usman.
“Setahun terakhir negara gagal membenahi kebijakan yang memicu protes. Dari soal pajak sampai tunjangan anggota DPR yang naik di tengah melemahnya ekonomi rakyat. Terkesan kuat, bukan hanya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan negara diabaikan, tetapi substansinya mementingkan kepentingan kalangan atas” kata Usman Hamid.
*Menguatnya militerisasi ruang sipil*
Dengan erosi terparah atas dua rumpun hak asasi di atas, Amnesty memperkirakan bahwa erosi atas hak asasi akan semakin parah. Salah satu faktornya adalah meluasnya peran militer di ruang-ruang sipil. Alih-alih memperkuat supremasi sipil, pasca Revisi UU TNI, kebijakan pemerintah membuka jalan bagi dwifungsi militer kemasan baru.
Rinciannya jumlah jabatan bagi perwira aktif meningkat 10 menjadi 16. Pembentukan 100 batalyon teritorial pembangunan, 20 brigade infanteri teritorial pembangunan, pelatihan transmigran sebagai komponen cadangan (Komcad), dan kompi produksi.
Jumlah komando teritorial bertambah dari 15 menjadi 21 Kodam bahkan menjadi 37 Kodam pada 2029. Setahun ini, ada 6 Kodam baru yaitu Kodam XIX/Tuanku Tambusai – meliputi Riau dan Kepulauan Riau, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – meliputi Sumatera Barat dan Jambi, Kodam XXI/Radin Inten – meliputi Lampung dan Bengkulu, Kodam XXII/Tambun Bungai – meliputi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kodam XXIII/Palaka Wira – meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Kodam XXIV/Mandala Trikora – berpusat di Merauke, Papua Selatan.
“Semua kebijakan itu menegaskan pola militerisasi pemerintahan yang mengaburkan area pertahanan dan non pertahanan. Belajar dari pengalaman, implikasi negatif bagi HAM-nya cukup serius,”
TNI kini bahkan terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial, mulai dari bertani, berternak, hingga memproduksi obat dan multivitamin. Padahal Indonesia tidak menyatakan keadaan darurat militer sehingga tugas itu semestinya dan sudah dijalankan oleh lembaga sipil.
Kecenderungan ini diperparah dengan keterlibatan TNI di proyek-proyek strategis nasional (PSN). Begitu pula penempatan purnawirawan militer di berbagai posisi strategis, dari 15 posisi kabinet hingga 5 dari 10 pimpinan Badan Gizi Nasional yang mengurusi MBG.
Di tingkat daerah, praktik-praktik seperti pengiriman siswa ke barak militer dan penerapan jam malam anak sekolah memperlihatkan perluasan logika militer ke ranah kehidupan warga sipil.
Tak hanya itu, sudah muncul upaya menjadikan TNI sebagai penyidik tindak pidana umum, yang seharusnya menjadi kewenangan aparat hukum sipil seperti polisi dan jaksa. Upaya ini terlihat dalam perumusan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (2)) serta Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (Pasal 56 ayat 1 huruf d).
“Menguatnya militerisasi atas ruang sipil ini mengikis profesionalisme militer, supremasi sipil, dan prinsip dasar HAM,” kata Usman Hamid.
Sebagai penutup, Amnesty menyimpulkan bahwa kebijakan maupun pernyataan pejabat negara cenderung mengabaikan aspirasi rakyat, dari resentralisasi ekonomi sampai pada remiliterisasi politik pemerintahan.
Negara seharusnya menjamin partisipasi rakyat, terutama dalam berekspresi. Berbagai kebijakan seperti proyek pembangunan dan industri ekstraktif yang mengancam alam dan masyarakat adat seharusnya dibenahi karena memperburuk ketimpangan sosial ekonomi.
Dalam menghadapi ketidakpuasan, negara cenderung membenarkan pendekatan represif bahkan menuduh pengunjuk rasa dengan label-label negatif yang semakin membenarkan pemolisian yang represif. Selain unjuk rasa akhir Agustus lalu, contoh lainnya adalah unjuk rasa bertema Indonesia Gelap yang juga dituduh didanai oleh koruptor.
Akar dari erosi hak asasi saat ini adalah arah kebijakan pemerintah saat ini yang pro-elite, menonjolkan praktik-praktik otoriter, militerisasi atas ruang sipil, efisiensi anggaran yang tidak tepat hingga mengenalkan kebijakan-kebijakan populis yang membebani anggaran seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih.
“Pemerintah pun kerap membungkam suara-suara warga yang mengritik kebijakannya lewat pemolisian yang represif. Jika tren ini berlanjut, maka Indonesia berisiko terperosok dalam otoritarianisme baru yang terus menindas hak-hak warga,” kata Usman.
Kebijakan negara dibuat tanpa partisipasi bermakna masyarakat, termasuk tanpa proses musyawarah mufakat yang memadai dari para wakil rakyat di parlemen. Ini diperburuk oleh pernyataan pejabat yang tidak berhati-hati dan tanpa kepekaan sosial.
Akibatnya terjadi erosi hak asasi manusia. Dari hak-hak sipil warga yang mengkritik dan protes lewat demonstrasi di perkotaan hingga hak-hak sosial masyarakat adat yang mempertahankan hak ulayatnya di pedesaan.